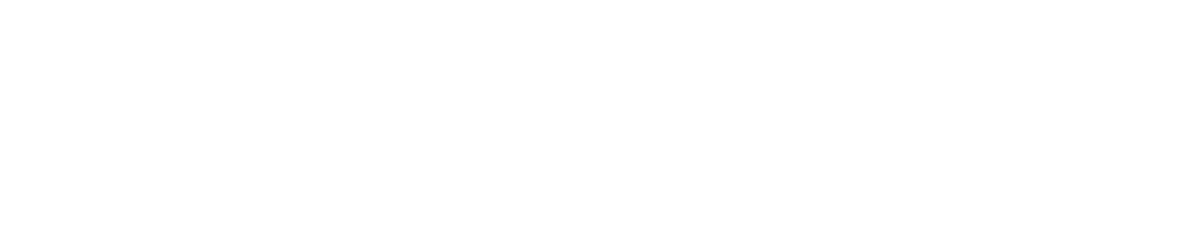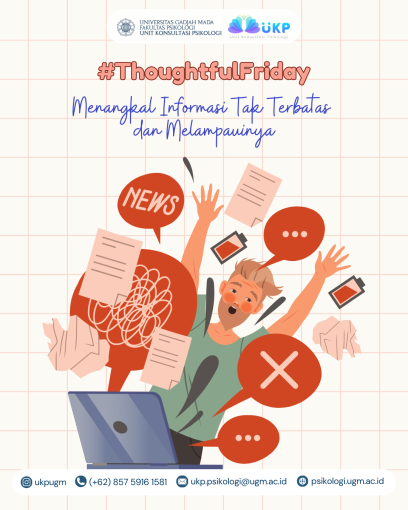
Dewasa ini, kemampuan yang kita miliki untuk mengumpulkan banyak informasi terkadang melaju erat dengan ketidakmampuan kita mengolah tumpukan informasi tersebut menjadi bahan yang bernilai guna. Ketidaksinkronan tersebut direpresentasikan oleh istilah information overload yang pertama kali diperkenalkan oleh Gross (1964) sebagai kondisi ketika jumlah informasi yang diterima sebuah sistem (biologis/nonbiologis) melebihi kapasitasnya untuk memproses informasi tersebut.
Fenomena information overload sendiri sulit dilepaskan dari pesatnya perkembangan teknologi yang senantiasa memperluas produksi serta aksesibilitas informasi. Bawden & Robinson (2020) melaporkan pencarian istilah information overload melalui Google menghasilkan jumlah lebih dari tiga juta item. Selain itu, pencarian melalui sebuah database literatur akademik—Web of Knowledge—menghasilkan sekitar 3.000 artikel bertopik serupa.
Di sisi lain, Bawden & Robinson (2009) menggambarkan informasi yang termuat dalam edisi mingguan New York Times pada awal abad ke-21 berjumlah lebih banyak daripada informasi yang terakumulasi oleh rata-rata orang Inggris pada abad ke-17 selama hidupnya. Di samping itu, informasi yang dihasilkan selama tiga dekade terakhir abad ke-20 memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan semua informasi yang terkumpul selama 5.000 tahun ke belakang.
Munculnya berbagai diskursus terkait fenomena information overload bukanlah tanpa alasan. Fenomena ini dapat menyebabkan efek negatif bagi sebagian orang, dibuktikan oleh adanya konseptualisasi terhadap akibat khusus dari ketidakmapuan seseorang memproses informasi berlebih, yaitu information fatigue syndrome dengan gejala berupa kesulitan tidur dan berpikir, cemas, hingga perasaan ragu terhadap diri sendiri yang intens (Goulding, 2001). Beberapa masalah kesehatan mental lain yang berkaitan dengan information overload adalah rendahnya kesejahteraan psikologis dan kepuasan hidup (Kominiarczuk & Ledinska, 2014).
Mengingat fenomena information overload berkaitan erat dengan karakteristik dunia modern yang tak dapat kita hindari, apakah ada cara untuk menyiasatinya? Savolainen (2007) menjelaskan teknik information withdrawal sebagai upaya sadar seseorang untuk meminimalisasi jumlah sumber informasi yang diproses. Contoh information withdrawal adalah ketika seseorang hanya mengikuti akun-akun media sosial yang terpercaya, menghindari eksposur terhadap konten yang tidak dirasa berguna, atau menonaktifkan akun media sosial sepenuhnya.
Bawden & Robinson (2020) menerangkan pula teknik filtering, yaitu proses menentukan relevan atau tidaknya informasi berdasarkan prioritas personal. Tujuan filtering adalah memfokuskan diri pada informasi yang dinilai penting sehingga atensi dan waktu yang dikerahkan seseorang untuk memproses informasi tersebut efektif. Contoh filtering adalah pembatasan interaksi di media sosial terhadap akun selain figur dekat atau sumber berita terpercaya untuk menghemat waktu dan daya fokus.
Selain itu, Poirier & Robinson (2013) menekankan sebuah pendekatan terkait pemrosesan informasi yang lebih berhati-hati untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kuat. Contohnya ialah ketika seseorang tidak serta-merta menyimpulkan informasi yang dikonsumsinya melainkan mengedepankan penilaian yang reflektif sebelum menilai.
Cara lain untuk menyiasati muatan informasi yang berlebih adalah melupakan atau “menghancurkan” sebagian besar informasi yang kita terima berdasarkan preferensi efektif. Hal itu didorong oleh tantangan kita saat ini untuk menentukan informasi mana yang perlu disisihkan di samping hanya menentukan saja informasi mana yang perlu dipertahankan.
Dalam menghadapi arus informasi yang tak terhindarkan di era modern, memahami dan mengelola information overload menjadi keterampilan penting. Dengan mengelola informasi secara bijak, kita tidak hanya melindungi kesejahteraan mental, tetapi juga menciptakan ruang untuk berpikir jernih, memahami lebih dalam, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Keterampilan ini berkaitan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG 3: Good Health and Well-being (Kehidupan Sehat dan Sejahtera).
Penulis: Alif Muhammad Abdillah
Bawden, D. & Robinson, L. (2009). The dark side of information: overload, anxiety and other paradoxes and pathologies. Journal of Information Science, 35(2), 180-191.
Bawden, D., & Robinson, L. (2020). Information overload: An overview.
Goulding, A. (2001). Information poverty or overload. Journal of Librarianship and Information Science, 33(3), 109-111.
Gross, B. (1964). The managing of organizations: the administrative struggles. New York: Free Press of Glencoe.
Hallowell, E. M. (2005). Overloaded circuits: why smart people underperform. Harvard Business Review, 83(1), 54-62.
Kirsch, D. (2000). A few thoughts on cognitive overload. Intellectica, 30, 19-51.
Kominiarczuk, N., & Ledzińska, M. (2014). Turn down the noise: Information overload, conscientiousness and their connection to individual well-being. Personality and Individual Differences, 60, S76.
Poirer, L. & Robinson, L. (2013). Informational balance: slow principles in the theory and practice of information behaviour. Journal of Documentation, 70(4), 687-707.
Savolainen, R. (2007). Filtering and withdrawing: strategies for coping with information overload in everyday contexts. Journal of Information Science, 33(5), 611-621.